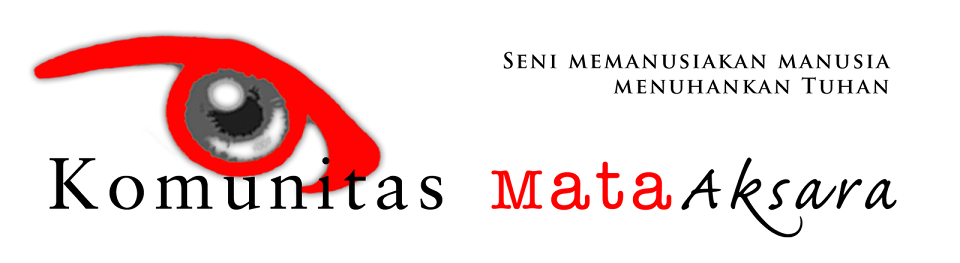Sura dan Perempuan
Cerpen Handoko F Zainsam (Republika, 17 Januari 2010)
 TAK
TAK seorang pun berani main-main dengannya. Dia perempuan terhebat yang pernah ada di negeri ini. Semua orang mampu dibuatnya jatuh cinta. Lantaran memburu cintanya, tak jarang terjadi silang sengketa, pertikaian, bahkan pembunuhan. Sungguh, tak seorang pun berani sembarangan menyebut namanya. Paling hanya menyerukan julukannya saja. Tak lebih, tak kurang. Ada yang menjulukinya Venus. Ada yang memadankan dirinya dengan Hera, Gaia, Maria, Hawa, atau Aisyah. Ada pula yang menyandingkannya dengan Sumbi atau Pariyem.
Begitulah. Perempuan itu tak henti-henti menghiasi halaman media cetak dan elektronik, bahkan merambah dunia maya. Di setiap jejaring sosial dan komunitas, namanya selalu sarat pikat dan penuh pukau. Ia jadi penghangat setiap perbincangan siapa saja dan di mana saja, baik lelaki maupun perempuan. Di hotel, di kantor, di salon, di pinggir jalan, bahkan di rumah-rumah ibadah. Ia adalah pengisi mimpi setiap laki-laki. Tak hanya petinggi negara, rakyat jelata pun terpesona pada kecantikannya. Bahkan, perempuan terpikat padanya. Ia permata yang tak pernah kehilangan pendar kilau.
Perempuan itu telah menjadi virus sosial yang mewabah. Keindahan rambut hitamnya yang tergerai panjang; keharuman tubuhnya yang meruah di segenap ruang meski ia telah berlalu; bening matanya yang menghanyutkan; bibirnya yang merona merah merekah; terlebih senyum indahnya yang belum pernah dilihat oleh siapa pun sebelumnya.
Konon, perempuan itu tinggal di sebuah tempat yang terjaga ketat. Tak seorang pun bisa dengan mudah mendekatinya. Apalagi menemuinya. Jika berniat melihatnya, pastilah harus menempuh jalan berliku dan penuh tantangan.
***
Mendengar kabar kecantikan perempuan itu, kaum lelaki berlomba mendapatkannya. Betapa tidak, semua lelaki meyakini perempuan itu adalah calon ibu terbaik bagi anak-anaknya, wanita paling teduh untuk dipinang menjadi istri, dan teman terkarib jika diangkat sebagai sahabat. Begitu halnya dengan seorang pembunuh bayaran kelas kakap dan buronan nomor wahid kepolisian. Lelaki begal yang ditakuti itu pun sangat terobsesi untuk menyunting perempuan itu. Sura, begitulah namanya diserukan. Identitasnya tak pernah jelas. Wajahnya saban waktu berganti rupa. Jangan harap ia bisa ditemukan dengan mudah. Polisi saja kewalahan mengejarnya. Dia tak pernah melakukan pola yang sama dalam setiap modus operandinya.
Tak ada kegagalan jika kita teguh melaksanakannya. Begitu prinsip hidupnya.
Demi perempuan itu, banyak yang berani membayar upahnya 10 kali lipat dari biasanya. Kali ini, semuanya ia tampik. Ia telah menentukan pilihan:
perempuan ternama itu harus jadi miliknya, apa pun risikonya.
Sungguh tak susah bagi Sura untuk melacak keberadaan perempuan dengan mata dan senyum terindah itu. Tak lebih dari 24 jam ia sudah berhasil menemukan di mana perempuan itu bermukim. Sura memang dikenal jenius. Daya ingatnya kuat. Ia mampu menghafal setiap informasi yang diserapnya dalam waktu singkat, dan dengan sigap mengolahnya menjadi muslihat baru untuk memuluskan strateginya.
***
Malam. Di perkampungan pinggir hutan dekat lokasi tujuan, Sura singgah di sebuah kedai. Seperti rumor yang berkembang, perempuan itu selalu menghiasi perbincangan warga. Tak susah mencari beritanya. Ia simak dengan saksama setiap obrolan pelanggan kedai. Tapi, ada yang janggal. Tak seorang pun keceplosan menyebut nama perempuan itu. Mitos yang berkembang, jika ada warga yang menyebut namanya, dalam jangka waktu singkat orang itu bakal menderita panas tinggi. Atau raib begitu saja. Musnah tanpa jejak.
Tapi, cukuplah rasanya kabar yang diserapnya. Sura pun bergegas merambah hutan lebat tanpa nama itu, hingga tiba di tepi sebuah sungai. Di seberang sungai menghampar hutan lebat lagi, lalu perkampungan tempat perempuan idamannya bermukim. Kali ini terasa lain. Sungguh, belum pernah ia merasa segugup ini. Detak jantungnya sangat kencang dengan irama tak beraturan. Belum lagi peluh dingin yang membanjiri jidatnya. “Ada apa ini,” keluhnya dalam hati. Ia menceburkan diri ke sungai, lalu mengguyur wajahnya. Dingin. Membekukan.
Selepas membasuh wajahnya, jantung Sura mulai stabil. Terang purnama memberikan cahaya cukup. Ia pun menyeberangi sungai dengan air setinggi lutut itu, lalu merambah hutan lagi. Tak terlihat sesiapa. Hanya sesekali terdengar
kowak burung hantu, geretak angin di ranting pinus, dan gemericik air sungai.
Tak dinyana, seekor musang meloncat jarak setombak di depannya, bergegas menghilang di rimbun semak. Seketika Sura makin berhati-hati. Hawa hangat meruap di pori-pori wajahnya. Hatinya waswas. Namun, petuah leluhurnya kembali meruyak ingatannya.
Jangan sekali-kali kau ragu. Ambil keputusan bermain atau tidak sama sekali. Sura menghapus keringat dinginnya, lantas melangkah penuh keyakinan menerabas hutan.
Tiba-tiba kesiur angin terasa menabrak pelipisnya.
“Siapa?” ucap Sura.
Tak ada jawaban. Hanya kesiur angin dan gemericik sungai terdengar membelah malam. Sepi. Sura kembali melangkah. Kemudian, samar-samar terlihat seorang laki-laki pendek bertelanjang dada. Pendek sekali orang itu, hanya setinggi pinggang Sura.
Nah,
akhirnya ketemu orang juga, batin Sura.
“Permisi, Pak,” sapa Sura.
Tak ada jawaban. Lelaki pendek telanjang dada itu masih duduk memunggungi Sura.
“Permisi. Izinkan saya lewat!” ucap Sura lagi.
Lelaki itu tetap membisu. Akhirnya, Sura menyadari siapa lelaki
kate itu.
Pasti Wong Alusan pengawal luar, katanya membatin. Seperti yang pernah diceritakan leluhurnya dulu, ia ingat apa yang harus dilakukan. Ia segera membalikkan badan dan berjalan mundur melewatinya. Ajaib. Tak terasa Sura telah berada di sebuah persawahan yang sangat luas. Kabut tipis yang turun sedikit mengganggu pandangnya.
“Di sini biasanya orang mati,” terdengar kalimat tanpa rupa pengucapnya.
Sura acuh. Dengan langkah pasti, dia berjalan menyusuri pematang sawah. Dia pun melihat seorang lelaki pendek dengan ikat kepala berdiri di pematang menghadap hamparan sawah.
Aneh, tengah malam buta kok berdiri di pematang, pikirnya.
“Maaf, Pak. Permisi, izinkan saya lewat,” sapa Sura.
Lagi-lagi tak ada jawaban. Sepertinya tak mendengar suara apa pun. Melihat itu, Sura berjalan menyamping, setapak demi setapak. Mendadak kabut turun teramat pekat. Sura tak mampu melihat apa yang ada di hadapannya. Sungguh perjalanan mencengangkan. Jauh dari kebiasaannya ketika menyelesaikan tugas sebagai pembunuh bayaran.
Dan, tiba-tiba saja pagi telah tiba.
Aneh. Kini, ia berada di sebuah taman bunga. Terlihat beberapa anak sedang mengejar kupu-kupu. Tak jauh dari tempat anak-anak bermain, sepasang petani sedang menyirami bunga aneka warna. Tapi, ganjil. Ia lihat anak-anak tersenyum dan bercanda, namun ia tak mendengar suara mereka. Ia lihat petani itu bercengkerama. Namun, lagi-lagi, ia tak mendengar suara mereka.
Sura tak menyia-nyiakan waktu. Ia bergegas menelusuri jalan menuju danau. Dilihatnya sebuah rakit bersandar. Di sebelahnya, di atas kursi dari batang
bamboo rangkap lima, seseorang tertidur. “Apa lagi ini,” ucap Sura lirih. “Pagi sudah cerah, orang ini masih tertidur lelap. Pasti
Wong Ndalem pengawal inti.”
Wajah orang itu tertutup caping. Tak lebih tiga langkah, Sura mengucap salam.
“Permisi, Pak. Izinkan saya menyewa rakit!”
Tak terdengar jawaban. Lelaki itu masih tertidur lelap.
“Izinkan saya menyewa rakit, Pak!” ulang Sura sembari melipat tangan di dadanya.
“Saya tidak menyewakan rakit!” jawab lelaki itu tanpa gerak.
“Izinkan saya meminjamnya.”
“Saya tidak meminjamkan!”
“Ajarkan saya mengemudikan rakit!”
Lelaki itu terbangun dan mendongakkan kepala. Alangkah terkejutnya Sura, lelaki itu memiliki wajah dan tubuh persis seperti dirinya. Tak ada sedikit pun yang beda. Gerak-geriknya, gayanya, bahkan tutur-sapanya. Sura terperanjat.
“Siapa kau?” tanya Sura spontan.
“Saya?”
“Ya!” tegas Sura.
“Naiklah ke rakit!” Terdengar suara itu berat dan kuat.
Sura seketika terdiam.
De javu.
“Apa ini!” serunya, “Aku ingat, ini kisah yang selalu ayahku ceritakan sewaktu kecil.”
Lalu, hawa lembut memilin-milin ulu hati, dan lutut Sura melemah. Terduduk, bersimpuh di hadapan lelaki kembarannya itu. Detik itu pula Sura tersungkur. Gelap. Semakin gelap!
***
“Bangun!”
Sura tertegun melihat sekelilingnya. Sekarang tubuhnya tergeletak di halaman rumah mungil yang mengambang di tengah danau. Ia bangkit perlahan-lahan. Menatap kembarannya dengan kebingungan.
“Saya hanya mampu mengantar sampai di sini. Masuklah!” kata lelaki itu, lalu membelokkan perahu setelah Sura menjejakkan kaki di tanah.
Dengan sisa-sisa tenaga, Sura mendekat. Belum sempat tangannya menyentuh, tiba-tiba pintu terkuak lebar. Terpampang pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ruang kosong. Melompong. Dan putih. Harum bunga melati seketika menyerang penciumnya.
Tak ada siapa pun. Ruang tanpa rupa. Tanpa kursi, tanpa meja. Tanpa sekat, tanpa kamar. Terang-benderang. Lembut, dan menguarkan kedamaian.
“Perasaan ini. Masa kecil. Aku tak bisa melupakannya.” Sura bergerak perlahan memasuki ruangan. Kenangan yang telah lama dikuburnya itu semakin membebat. Kasih sayang itu terus menggedor-gedor pintu batinnya. Semakin lama semakin kuat. Hingga tak mampu lagi ia menahannya. Ia tersungkur. Lamur. Pandangannya mengabur.
***
Sura, lelaki peringkat pertama daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian yang disegani dan ditakuti banyak orang, sekarang tersungkur tanpa daya. Lelaki yang bisa mencabut nyawa orang seenak perutnya itu sekarang tak bisa apa-apa. Kini, di rumah perempuan idamannya, perempuan incaran untuk disunting sebagai istri, berdiri saja ia tak sanggup. Hanya bisa pasrah.
Dan, begitu kelopak matanya terbuka, perempuan itu berdiri semampai tiga langkah di depannya. Hanya tiga langkah, tapi ia tak mampu menjangkaunya. Dan senyum itu, oh, senyum itu begitu indah. Belum pernah ia melihat senyum seindah itu. Benarlah kiranya kabar yang beredar. Perempuan dengan mata dan senyum terindah itu pun merentangkan tangan seperti ingin memeluknya.
Tapi, penglihatan Sura kembali lamur. Makin lama makin kabur.
“Ibu!” Terdengar suara lirih itu dari mulutnya.
Tak lama, ruangan seketika menjadi gelap. Pekat. Amat pekat.
(*)
-----------------------------------------------------------------------
Handoko F Zainsam, penggagas dan pendiri Komunitas Mata Aksara (KomMA) Jakarta. Karya-karyanya: I’m Still a Woman tahun 2005 (novel); Antologi Puisi Kota Sunyi Tahajud Cinta Kunang-Kunang (2009).